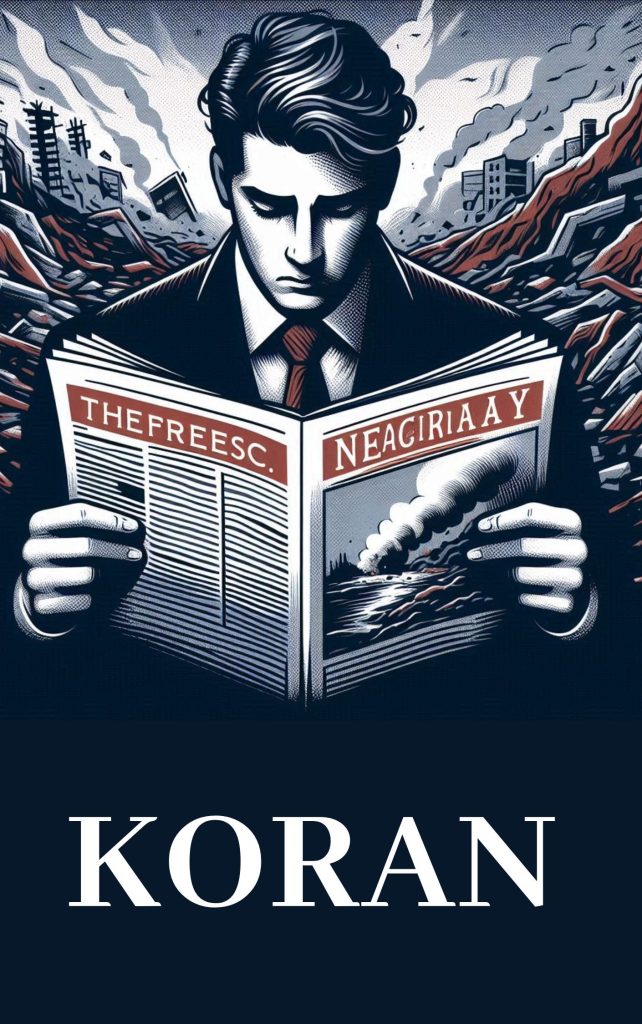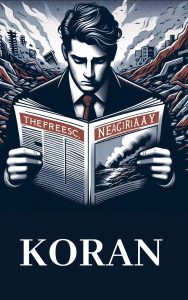
Halaman
191
Tanggal Terbit
2009
ISBN
9789791915441
Penerbit
ANPH
Aku mencintai koran. Bagiku koran menjadi pusat infor- masi. Berita apa saja nyaris tak pernah luput dari jang- kauannya. Tentang daerah bencana yang menelan ratusan korban jiwa, tentang tempat hiburan yang hanya terjangkau oleh orang-orang berduit, sampai tukang becak yang mencalonkan diri menjadi gubernur DKI.
Jadi, kalau aku ingin tahu apa yang terjadi di mana saja, cukup memanggil penjual koran eceran, menyerahkan tiga lembar uang ribuan, lalu asyik berjam-jam berkeliling ke berbagai daerah yang diberitakan.
Koran juga teman yang paling setia. Dia hadir setiap hari, kecuali hari-hari besar tentu. Saking setianya pada koran, teman-temanku sering menertawakan kebiasaanku yang satu itu.
“Orang kecil kayak kamu, sok baca koran, Din!”
Mas Parjo, tukang bakso yang juga teman sekamarku di rumah kontrakan sempit itu, meledek.
Biasanya aku tak mau kalah, cepat membalas ledekan- nya, “Orang kecil kayak kita, bisanya ya memang sok tahu, Mas! Mau sok pamer kan enggak bisa.”
Jawabanku yang terkesan asal saja melahirkan tawa terbahak-bahak. Meski tak jarang malah menimbulkan komentar lain. Bang Sani, tukang parkir di Pasar Ikan Muara Angke, misalnya, lain lagi pendapatnya.
“Apa yang menarik dari koran, Din? Tak paham aku. Paling longsor sana, kebakaran sini. Gunung meletus, bom meledak….”
“Demo!” Mang Usup menambahkan. Bang Sani mengangguk-angguk.
“Ya, demo. Lalu apa lagi? Paling berita harga BBM, tarif listrik, dan tarif telepon yang naik serentak! Korupsi yang susah diberantas! Mana ada berita yang enak dibaca? Isinya kesengsaraan semua begitu kok!” protes Bang Sani.
“Lho…, kok Bang Sani sama Mang Usup tahu semua isi koran?” tanyaku sambil memasang muka lugu. Di depanku, agak tersipu, mereka berdua menjawab, “Yaa… gini-gini kami baca koran juga!”
Walah, aku mencibir.
Bang Sani buru-buru membela diri, “Tapi aku kan tidak tiap hari kayak kamu, Din!”
Mungkin di mata mereka, penghasilanku yang cuma guru madrasah, tidak pantas dihabiskan untuk membeli koran setiap hari.
“Kalo gua, mending buat beli rokok dah!” Japra, preman yang sering nongkrong di daerah bongkaran Tanah Abang, ikut mengomentari.
“Rokok apa rokok, Pra?” Mang Usup nyamber. Maklum, wilayah kekuasaan Japra memang terkenal sama pelacur kelas teri yang biasa memberi servis dengan harga miring, big sale istilah kerennya, terutama setiap tanggung bulan.
Terlepas dari komentar mereka, membaca koran bagiku adalah kebutuhan dasar yang tidak terelakkan. Hiburan yang mencerdaskan.
“Koran itu bikin kita cerdas!” ucapku berkali-kali me- nyitir moto sebuah media ibu kota. Atau di kesempatan lain, “Koran itu enak dibaca dan perlu!” suaraku keras dan penuh semangat, meski masih sama tidak kreatifnya, karena lagi-lagi cuma mencomot slogan koran.
Aku begitu mencintai koran. Soalnya mau mencintai yang lain, lalu menikah, aku belum mampu. Meski putri Pak Suleman, merbot di masjid tua dekat tempat tinggalku, sudah berkali-kali secara halus mendekati.
“Jangan mau sama Si Udin, Munah! Dia itu cintanya cuma sama koran”
“Tak ada yang bisa menggetarkan hatinya kecuali judul-judul di koran!”
“Mending sama gua, Mun!”
Bertubi-tubi Mang Usup, Bang Sani, dan Japra ber- usaha menghancurkan pasaranku di depan Munah, anak merbot itu. Tapi di telingaku, komentar mereka justru membuatku bangga.
Orang cerdas itu baca koran, tau!
Tapi perasaanku pada koran, mulai terganggu tiga bulan yang lalu. Uniknya bukan karena omongan kawan- kawan. Penyebabnya justru berasal dari koran itu sendiri.
Waktu itu aku sedang menyisir judul-judul berita tiap halaman, ketika mataku tertumpu pada satu berita, “Guru SD di Bogor Dikeroyok Massa karena Mencabuli Anak Didik.”
Kubaca isi beritanya lebih karena dorongan naluri.
Guru SD bernama Maman Jumadi, 30 tahun, dike- royok massa setelah salah satu muridnya mengadu telah di- perlakukan tidak senonoh… Bapak dari tiga anak tersebut, saat ini meringkuk di Polres Bogor.
“Hei…, mau ke mana, Din?”
Teriakan Mas Parjo yang sedang menyiapkan gerobak- nya tak kupedulikan. Secepatnya aku berlari menuju wartel. Keluar dari sana, badanku lemas. Kliwon, teman sekelas di SPG dulu, yang kuhubungi membenarkan duga- anku.
“Betul, Din. Itu Maman kawan kita. Kabarnya malah ini bukan yang pertama kali dia begitu. Kacau juga dia, ya!”
Kabar itu begitu memukulku. Teringat istri Maman yang lembut dan pendiam, juga anak-anaknya yang lucu. Setahun yang lalu aku masih sempat mengunjungi mereka sekeluarga di Bogor. Ahh…, Maman! Kenapa dia jadi brengsek begitu?
“Itulah hidup, Din! Cobaan di mana-mana. Kalo tidak kuat iman, yah… begitu!”
Mas Parjo menghiburku. “Sudah jangan sedih. Nih aku belikan kamu koran sore!”
Aku tersenyum. Menerima gulungan koran dari Mas Parjo. “Beli, Mas?”
Ini kejadian pertama Mas Parjo membeli koran. Lelaki kurus berkulit gelap yang bujang lapuk itu tertawa men- dengar pertanyaanku.
“Enggak, beli. Nyamber, Din!”
Aku tersenyum.
“Wis, yah… aku mau keliling lagi. Bakso belum habis. Kayaknya sekarang orang-orang kok ya lebih seneng makan di mal daripada jajan bakso,” keluhnya sebelum men- dorong gerobak.
Setelah Mas Parjo pergi, aku sendirian di kamar. Pi- kiranku menerawang ke Maman dan keluarganya. Kasihan betul mereka. Si Maman itu dari dulu sepertinya memang punya hasrat berlebih. Sejak sekolah pun sering aku pergoki dia dengan perempuan, di belakang sekolah.
Pernah juga Kliwon cerita padaku, bagaimana Maman “main” di gang gelap tempat dia tinggal. Mentang-mentang malam sepi. Seenaknya saja. Dua insan yang bercumbu itu terkaget-kaget, ketika tukang nasi goreng lewat dan mendadak membunyikan tok tok-nya.
Kuraih koran pemberian Mas Parjo. Kubaca perkem- bangan kebijaksanaan Amerika Serikat terhadap warga muslim di sana, lalu komentar beberapa anggota DPR soal naiknya harga-harga menyusul kenaikan BBM, telepon, dan tarif listrik, sedang para konglomerat yang utangnya trilyunan malah dibiarkan bebas. Sungguh ajaib keadilan yang diberikan aparat pemerintah pada rakyatnya.
Kubuka halaman demi halaman. Kubaca satu demi satu. Bagiku koran yang kucinta bukan barang memang murah, jadi harus diperlakukan seperti makanan. Tak ada yang boleh terlewat. Siapa tahu berita yang membawa berkah malah ditaruh belakangan. Jadi, aku terus mem- baca.
Sampai halaman empat, aku terpaku. Mendadak ba- yangan Japra dengan tato-tato di sekujur lengan dan pung- gungnya, melintas. Japra yang lebih suka membeli rokok daripada membeli koran.
Dan kemarin, dalam keributan antara preman Tanah Abang, jagoan bongkaran itu tewas dibacok!
Aku terpukul. Rasanya ada bongkahan batu besar yang dipukulkan ke dadaku berulang-ulang. Teman mainku dari kecil meninggal dan aku harus mengetahuinya lewat koran sialan ini?
“Lo sih enggak nongol-nongol, Din!”
Mang Usup menyambut kedatanganku. Masih di gardu tempat kami biasa ngobrol.
“Sibuk apaan sih, Din?”
Aku tak menjawab. Dadaku masih sesak. Barusan istri Japra yang kutemui menubrukku dan menangis tersedu- sedu. Perempuan yang dinikahi Japra lima tahun lalu itu, tampak sangat kehilangan.
“Biar gimana dia laki yang baik, Din! Sayang sama anak-anak,” suara Mbak Karsinah panjang-pendek, me- nyisakan kesedihan pada ruang-ruang batinku.
Sejak itu aku mulai enggan membaca koran. Kubiar- kan saja loper koran langgananku terbengong-bengong menerima penolakanku atas koran yang ditawarkan.
Pernah sekali, karena iba pada bocah penjual koran yang baru berusia 10 tahun itu, aku mengalahkan keeng- ganan. Akibatnya?
…salah seorang buronan yang diduga terkait jaringan pemboman di Makasar, berinisial MS, sehari-hari dikenal sebagai tukang parkir di Muara Angke…
MS? Tukang parkir Muara Angke? Muhammad Sani, Bang Sani? Bom? Kapan pula lelaki itu ke Makasar?
Masya Allah. Perasaanku gonjang-ganjing. Rekayasa aparat keamanankah? Tuduhan asalkah untuk sekadar mencari kambing hitam? Atau memang aku yang tidak cukup memahami teman?
Lemas, kupandang lembar demi lembar koran yang masih kupegang. Aku sendiri tidak tahu, mana yang sebetulnya lebih menyesakkan dada. Koran memberita- kan? Atau mereka sang pembuat berita?
Kubuang koran dari tanganku. Keinginan untuk mem- bacanya langsung menguap.
Begitulah, sudah tiga bulan aku memusuhi koran. Mungkin bukan memusuhi, tapi terhantui. Koran menjadi hal yang mengerikan bagiku. Bagaimana jika kutemui lagi berita-berita yang menyangkut orang-orang yang kukenal? Sanak kerabat, teman-teman dekatku? Bagaimana jika nanti justru namaku yang terpampang di sana dengan tuduhan meledakkan bom di mal?
Dari hari ke hari, aku semakin membuat jarak yang tegas dengan koran. Tidak hanya itu, aku pun jadi malas menonton berita di TV. Dunia sunyi tanpa berita, mungkin menjadi pilihan hidupku sekarang.
“Pokoknya aku tidak mau baca koran lagi. Titik!” tegas suaraku mengagetkan Mas Parjo yang barusan mengulur- kan koran dengan oplah paling tinggi di negeri ini. “Ooh…, belum damai to?”
“Pokoknya tidak!”
“Koran yang pagi, apa koran sore?”
Kalimat yang diucapkannya sambil bercanda itu tak mendapatkan reaksiku.
“Wis. Ndak mau, ya sudah! Ndak usah marah!”
“Mas Parjo maksa sih,” sahutku belakangan, kesal.
“Aku keliling dulu, ya? Dibawakan koran, udah capek- capek nyamber, bukannya makasih.”
Aku diam saja. Meski ketika sosok kurusnya keluar rumah, aku sempat melongokkan kepala lewat jendela dan meminta maaf atas kekasaranku.
Masih dengan senyum khasnya, Mas Parjo hanya me- ngibaskan tangan, “Ndak ара-ара. Aku jalan dulu, yo?
Malam itu aku tidur sendirian. Mas Parjo tidak pulang, gerobaknya pun tak nongol. Mungkin menginap di tempat keponakannya, seperti biasa. Namun ketika besok dan besoknya, tukang bakso asal Pemalang itu, tidak juga muncul. Aku mulai panik.
Di depanku tergeletak surat kabar terbaru, yang baru saja kubeli dengan sangat terpaksa. Tujuannya cuma satu: mencari jejak Mas Parjo.
Lima belas menit. Setengah jam. Satu jam.
Aku masih memandangi koran di atas meja. Hatiku maju-mundur. Bagaimana jika kubuka lembar-lembar berita itu dan menemukan nasib Mas Parjo, sahabatku itu di sana? Seperti apa beritanya kira-kira?
Tukang bakso tewas setelah menyambar celana Levi’s? Memperkosa? Ahh, rasanya tidak. Mas Parjo orangnya sopan dan tidak kurang ajar pada perempuan. Lalu apa? Buka saja!
Tidak mau!
Buka!Aku belum siap!
Dua sisi hatiku berperang, bagai mata uang yang masih melambung setelah dilemparkan ke udara. Belum ada pemenang.
Buka!!!
Dengan mengumpulkan semua keberanian, aku meraih koran cepat-cepat, lalu membukanya tanpa berpikir.
Halaman pertama aman. Kedua juga aman. Tidak ada berita tentang tukang bakso yang mati terlindas kereta. Halaman ketiga, masih seputar pengusutan korupsi yang tidak selesai-selesai. Halaman keempat, kelima, keenam….. seterusnya hingga halaman dua belas, aku menarik napas lega.
Tapi… tunggu dulu!
Kalau tidak salah, ada satu halaman yang terlewat.
Maka kubuka lembar demi lembar. Kubaca halaman demi halaman. Meski dengan hati yang lebih lapang.
Halaman sembilan. Dadaku mendadak seperti ter- tancap belati.
Ucapan salam di pintu depan dan langkah riang dua anak manusia memasuki rumah sewaku, tak kupedulikan, “Din! Aku nikah, Din!”
Mas Parjo dan gadis manis berambut sebahu di sampingnya tersenyum malu-malu. Aku masih diam. Perih. “Din! Wah… marah kamu, ya, ndak dikasih tahu? Kejadiannya begini…”
Mas Parjo masih bercerita panjang lebar. Tapi belati
di dadaku menancap kian dalam, menimbulkan nyeri yang tak terhingga.
Halaman sembilan… Tuhan…
Emak, dan adik-adikku. Nama mereka semua ter- cantum dalam daftar korban tanah longsor, dua hari yang lalu.